Ijtihad Pada Masa Abu Bakar (Sebuah Tinjauan Sosio-Historis)
Sunday, 24 January 2016
Sudut Hukum | Ijtihad
Pada Masa Abu Bakar (Sebuah Tinjauan Sosio-Historis)
Ajaran Islam yang bersumber dari dua pusaka,
al-Qur’an dan Hadis, diyakini sebagai tuntunan setiap prilaku umat manusia.
Tidak ada sedikitpun perbuatan manusia yang dapat lepas dari kontrol shari’at.
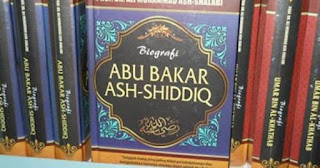 Demikian itu dapat dilihat dari sikap mental
para sahabat Nabi SAW dalam menjalankan dan mengawal kemurnian ajaran-ajaran
agama dalam kehidupan. Tidak akan ditemukan prilaku dan perbuatan mereka yang
tidak memiliki pembenaran al-Qur’an dan percontohan dari Hadis Nabi SAW. Para
sahabat tidak akan melakukan inovasi dalam urusan yang berkaitan dengan masalah
keagamaan, jika tidak memiliki landasan teologis yang memanyunginnya, baik dari
al-Qur’an atau dari Hadis.
Demikian itu dapat dilihat dari sikap mental
para sahabat Nabi SAW dalam menjalankan dan mengawal kemurnian ajaran-ajaran
agama dalam kehidupan. Tidak akan ditemukan prilaku dan perbuatan mereka yang
tidak memiliki pembenaran al-Qur’an dan percontohan dari Hadis Nabi SAW. Para
sahabat tidak akan melakukan inovasi dalam urusan yang berkaitan dengan masalah
keagamaan, jika tidak memiliki landasan teologis yang memanyunginnya, baik dari
al-Qur’an atau dari Hadis.
Sementara itu, umat Islam sepeninggal Nabi
mulai dihadapkan pada persoalan-persoalan baru yang memerlukan jawaban-jawaban
teologis sebagai tantangan bagi elastisitas ajaran Islam sebagai ajaran yang salih li kull zaman wa makan. Persoalan-persoalan baru itu muncul sebagai konsekwensi
logis perkembangan sosio-kultural dan sosio-politik umat yang sangat
dinamis, dikarenakan makin luasnya ekspansi Islam serta perubahan situasi dan
kondisi (zuruf) yang mengitarinya. Tidak semua permasalah-permasalahan
itu memiliki preseden pada Hadis Nabi. Bahkan banyak di antaranya yang
betul-betul baru yang tidak memiliki petunjuk praktis keagamaan.
Dari sinilah kemudian, para sahabat Nabi SAW
tidak memiliki pilihan lain untuk tidak melakukan ijtihad.[1] Oleh karena itu pula
ulama sepakat bahwa hukum ijtihad adalah fardu kifayah yang berarti melarang
adanya kekosongan suatu masa dari kegiatan ijtihad.[2]
Ijtihad Dan Masalah Itjihadiyah
Ijtihad didefenisikan sebagai upaya dari
al-faqih secara sungguh-sungguh dalam menggali hukum shari’at far’iyah dari
dalil-dalilnya.[3] Catatan penting dari
defenisi ini adalah bahwa kata-kata “upaya sungguh-sungguh” mengecualikan
persoalan-persoalan yang dapat diketahui dari agama secara daruri yang tidak
membutuhkan “daya besar” untuk memahaminya.
Sedangkan medan ijtihad adalah setiap
persoalan hukum shari’at yang tidak memiliki dalil pasti. Namun sebenarnya,
menurut Menurut Muhammad Yusuf al-Qardawi, medan ijtihad tidak terbatas pada
persoalan hukum saja sebagaimana pendapat usuliyin. Sehingga baginya medan
ijtihad meliputi semua permasalahan shari’at yang tidak memiliki dalil pasti (qat’iy al-thubut wa al-dalalah), baik menyangkut masalah usuliyah
i’tiqadiyah atau masalah far’iyah ‘amaliyah[4].
Namun bisakah diterima bahwa sesuatu yang
penting dalam urusan agama ditinggalkan dan tidak dijelaskan oleh sumber
otoritas shari’at. Padahal Nabi SAW telah mengajarkan banyak persoalan, baik
besar atau kecil, sampai pada persoalan apa yang harus diperbuat seorang muslim
dalam wc. Kita ambil contoh masalah khilafat al-Rasul yang menyebabkan
munculnya friksi keras antara sesana umat.
Dalam hal ini, Doktor Muhammad Ahmad Khalf
Allah punya pandangan, sebagaimana dikutip Khalil ‘Abd al-Karim, bahwa banyak
hal yang tidak dijelaskan oleh teks-teks keagamaan padahal menyangkut persoalan
yang sangat penting karena suatu hikmah yang tersembunyi, yaitu memberi ruang
kepada akal manusia untuk berijtihad sesuai situasi dan kondisi (zuruf al-zaman wa zuruf al-makan) dan sesuai pula dengan kesadaran pikirannya
berdasarkan tanggungjawab masing-masing.[5]
Inilah sebenarnya yang menjadi salah satu ketentuan hukum Islam yakni bahwa Allah SWT membatasi taklif dan meluaskan ruang kosong kemaafan (mantiqat al-‘afw) untuk memberi ruang bagi ijtihad.[6]
Metode Ijtihad Sahabat
Berbeda dengan kondisi dan situasi pada masa
Nabi, pada masa sahabat banyak timbul kejadian yang tidak ada pada masa Nabi
yang mengharuskan mereka untuk melakukan ijtihad. Menurut Mahdi Fadl Allah[7] ada tiga langkah yang
dilalui oleh para sahabat dalam berijtihad ketika dihadapkan pada permasalah
baru. Pertama, mengidetifikasi persoalan yang muncul dengan melihat teks
al-Qur’an untuk mengetahui apakah perosalan baru itu terdapat di dalamnya.
Jika tidak ditemukan ayat yang berkaitan
dengan masalah yang muncul, langkah kedua melihat Hadis. Dikumpulkannya para
sahabat untuk minta keterangan tentang apakah mereka mendengar sesuatu dari
Nabi berkaitan dengan masalah yang dihadapi. Seperti ketika Abu Bakr ditanya
tentang bagian waris nenek, yang pertama ia lakukan adalah mencari ayat
al-Qur’an yang berkenaan dengna masalah waris. Ketika ia tidak berhasil
mendapatkannya, lalu ia kumpulkan para sahabat untuk dimintai keterangan
tentang apakah ada riwayat Nabi SAW tentang bagian waris nenek. Lalu al-Mughirah
bersaksi bahwa Nabi SAW memberinya seperenam. Pernyataannya kemudian diperkuat
oleh keterangan Muhammad ibn Maslamah. Kemudia Abu Bakr menetapkan
seperenam untuk nenek.
Jika melalui langkah kedua ini tidak berhasil,
kemudian mereka bermusyawarah untuk melakukan ijtihad secara hati-hati dengan
menggunakan ra’yu pada batas-batas yang dapat mengungkapkan keinginan al-Shari’
berupa jalb al-masalih wa dar’u al-mafasid.
Penggunaan ra’yu di sini bisa berarti qiyas,
maslahah dan lain sebagainya yang intinya adalah mengidentifikasikan hukum
suatu perbuatan manusia yang tidak memiliki keterangan dari teks-teks
keagamaan.[8]
Oleh karena adanya batas-batas penggunaannya
itu, seorang islamisis J. Schacht berpendapat bahwa prinsip-prinsip istihsan,
maslahah dan lain sebagainya sebenarnya tidak dapat digunakan sebagai prinsip
yang independen tetapi lebih untuk menafsirkan dan menjustifikasi aturan hukum
Islam yang sudah ada yang dimaksudkan untuk membangun zona perlindungan di
sekitar perubahan itu agar ia tidak kehilangan keseluruhan teori itu.[9]
Legalitas Ijtihad Sahabat
Di masa Nabi, ketika muncul permasalah para
sahabat langsung bertanya padanya atau jika kebetulah posisi Nabi jauh, mereka
berijtihad kemudian menyampaikan hasil ijtihad mereka kepada Nabi. Sehingga
semua persoalan menjadi jelas dan gamblang antara yang ditetapkan atau yang
dikoreksi, karena Ia memiliki otoritas penuh untuk tashri’.[10]
Sekalipun hanya Nabi SAW yang memiliki
otoritas tashri’, ia tidak pernah mencela apalagi melarang tindakan ijtihad
para sahabat. Justru sikap yang ia tunjukan menunjukkan apresiasinya terhadap
tindakan itu. Hal itu memberi pengertian bahwa ia memberi restu kepada para
sahabatnya untuk berijtihad.[11]
Namun setelah Nabi wafat tidak ada lagi
otoritas semacam itu. Karena posisi Nabi SAW sebagai nabi dan rasul tidak dapat
digantikan oleh siapapun. Dengan demikian, apa yang dilakukan oleh para
pengganti kepemimpinan Nabi (khulafa‘ al-Rasul) hanya mencari justifikasi
penyelesaian setiap persoalan yang muncul dengan al-Qur‘an dan Hadis. Namun
jika tidak didapatkan petunjuk dari keduanya, mereka berijtihad dengan cara
bermusyawarah dengan para pembesar sahabat yang lain. Periode ini disebut masa
al-tafsir al-tashrii’ yang berarti masa rintisan praktek istinbat terhadap
hukum masalah-masalah yang tidak memiliki petunjuk praktis keagamaan[12] dan inilah yang
menandai awal dimulainya periode fiqh pertama dalam sejarah hukum Islam.[13]
Menurut al-Sayis, ijtihad sahabat ini punya
makna luas. Kegiatan ijtihad mereka itu meliputi pencarian teks keagamaan
sesuai permasalah, melakukan qiyas, istihsan, sadd al-dharai’,
maslahah mursalah dan
seterusnya.[14] Namun istilah-istilah
belum muncul pada saat itu sebagai khazanah istilah hukum Islam kecuali pada
masa imam-imam madzhab.
Berkaitan dengan kekuatan fatwa sahabat, ulama
al-madhahib al-arba’ah pada fatwa sahabat sepakati memeganginya kecuali Abu
Hanifah memberi catatan bahwa tidak boleh menyalahi pendapat sahabat yang tidak
diketahui adanya ikhtilaf di antara mereka.[15] Ini berarti bahwa
pendapat sahabat yang demikian, dalam istilah Muhammad Musa Tuwana, asbaha taqriban masdar thalithan (menjadi sumber ketiga).[16]
Setting Sosial Masa Sahabat
Sepeninggal Nabi SAW yang dirasa para sahabat
terlalu cepat, keadaan sungguh berubah. Mereka seperti bayi yang tiba-tiba
disapih oleh ibunya pada saat ia masih merasakan keberadaannya sangat
dibutuhkan. ‘Umar Ibn al-Khattab mungkin orang yang paling tidak bisa
sanggup menerima keadaan yang menggoncangkan jiwanya ini. Sehingga ucapannya
pun “barang siapa yang berkata Muhammad mati akan saya tebas lehernya” membuat
keadaan jadi tidak menentu. Akan tetapi Abu Bakr kemudian tampil di hadapan
halayak yang justru menegaskan bahwa Nabi tercinta mereka benar-benar telah
wafat seraya ber-istidlal pada ayat 144 surat ‘Ali ‘Imran. Sikap Abu
Bakr inilah yang dicatat sebagai penafsiran/ijtihad pertama kali yang dilakukan
pasca masa Nabi dalam sejarah Islam.[17]
Selanjutnya para sahabat dihadapkan pada
banyak masalah yang baru dalam Islam dari persoalan khilafah, pemberontakan,
penolakan membayar zakat, nabi palsu, pembagian rampasan perang, terbunuhnya
para huffad dan lain-lain dari
persoalan keagamaan sampai masalah pemerintahan dan keuangan dari yang kecil
sampai yang besar.
Yang menjadikan betapa beratnya tugas para
sahabat sepeninggal Nabi disebabkan oleh beberapa kondisi. Pertama,
di masa Nabi, syari’at Islam dalam aspek hukum diterapkan sebagai hukum
masyarakat. Dalam diri Nabi terdapat dua otoritas sekaligus, kekuasaan agama
dan politik yang tidak dipisah-pisahkan. Keadaan ini tentu tetap dipegang erat
oleh mereka.[18]
Kedua, sikap rigid mereka
untuk tidak berbuat sesuatu yang tidak pernah dicontohkan Nabi, seperti sikap
Abu Bakr ketika diberi masukan tentang perlunya mengumpulkan al-Qur’an dalam
satu mushaf “kayfa naf’al shay’an lam yaf’alhu
rasul Allah SAW?!”.[19]
Ketiga, dorongan internal
untuk menjalankan dan mengawal kemurnian ajaram Islam sebagai tugas utama khalifat al-Rasul. Keempat,
sementara faktor eksternal seperti muncul masalah-masalah baru menuntut respon
dan solusi yang mempunyai landasan teologis.
Contoh Ijtihad Pada Masa Abu Bakr Ra.
Sesuai dengan beberapa paparan di muka,
di sini akan disajikan beberapa contoh kasus yang terjadi pada masa Abu Bakr
yang diselesaikan secara ijtihad khususnya menggunakan pendekatan qiyas,
maslahah mursalah[20] dan sebagainya yang
intinya menemukan hukum dari masalah-masalah yang tidak terdapat dalam nas.
- Memerangi Orang-Orang Yang Menolak Membayar Zakat
Ketika Nabi wafat dan Abu Bakr diangkat
sebagai khalifah, banyak persoalan muncul. Diantaranya yang dianggap besar
adalah orang-orang yang menolak membayar zakat pada khalifah. Penolakan mereka
itu punya implikasi politik yakni tidak mengakui kesinambungan dan
peralihan kepemimpinan Nabi kepada Abu Bakr. Munculnya gagasan memerangi dan
memperlakukan mereka sebagaimana orang-orang murtad ditolak ‘Umar. Ia menolak
mengekskusi mereka karena tidak mungkin membunuh orang yang nyata-nyata
bersahadat berdasarkan Hadis ‘umirtu annla
‘uqatil al-nas hatta yaqulu La ila illa Allah (al-H{adith).[21]
Dalam pandangan Abu Bakr membiarkan penolakan
mereka berarti membiarkan rongrongan pada legalitas kepemimpinannya yang
berarti kesatuan umat dalam ancaman disintegrasi. Karena Abu Bakr melihat zakat
bukan sekedar ibadah yang cukup dilaksanakan dengan tanggungjawab secara
vertikal saja, ia melihatnya sabagai urusan publik. Oleh karena harus ada
otoritas yang menangani, karena zakat adalah salah satu sumber keuangan
publik sekaligus sebagai jalan pembelanjaan publik yang memiliki ciri yang
khas.
Tugas pemerintahan Abu Bakr dalam kaitan zakat
ini adalah menjaga keadilan distribusi kekayaan. Ini dapat dilihat dalam
prakteknya bahwa yang diperangai Abu Bakr adalah orang-orang yang menolak
membayar zakat harta dahir yaitu zakat mawashi (perternakan, tidak harta
yang tersembunyi seperti emas dan perak. Dengan demikian jelaslah bahwa
pertimbangan perang ini lebih bersifat politis.
‘Umar yang pada awalnya menolak, akhirnya
menerima argumentasi Abu Bakr.[22]Karena ia melihat sikap dan tindakan
Abu Bakr ini sangat dipengaruhi situasi umat dan stabilitas yang tidak kondusif
setelah ditinggalkan oleh Nabi, bukan sekedar pertimbangan teologis semata.
Jadi setiap bentuk penyimpangan akan sangat besar pengaruhnya terhadap keutuhan
politik umat. Untuk itu, demi menjaga stabilitas, sikap Abu Bakr menjadi sangat
tegas dan tidak kompromi.
- Pengumpulan al-Qur’an Dalam Satu Mushaf
Gagasan ini merupakan masukan ‘Umar. Pada mula
Abu Bakr menolak, namun akhirnya ‘Umar dapat meyakinkannya sehingga ia
memutuskan untuk melakukan jam’u al-Qur’an fi mushaf wahid [23] karena dirasakannya
manfaat yang besar dan kerugian yang besar bila tidak dilakukan. Hal itu
setelah disadari bahwa hafalan yang terkuat lebih rendah dari tinta terlemah
untuk menjaga otentisitas dan keutuhan kitab suci
setelah banyak para huffaz yang terbunuh dalam peperangan. Disamping itu,
pengumpulan al-Qur’an dalam satu mushaf berfungsi sebagai penjagaan di
dalam menghindari kemungkinan adanya penyelewengan, perbedaan dan lain-lain
yang dapat mengurangi kesakralan al-Qur’an sebagai kitab suci.
- Mendirikan Lembaga Keuangan Bayt al-Mal [24]
Keputusan ini tentu tidak akan dapat dilacak
secara langsung dalam teks-teks keagamaan, namun manfaatnya sangat besar bagi
keuangan umat/negara. Hal ini juga merupakan akibat munculnya lembaga baru
dalam sejarah Islam yaitu lembaga khilafah. Sementara di masa Nabi sistim
pemerintahan dijalankan dalam bentuk yang sangat sederhana dan unik. Tantangan
kemajuan umat Islam pada masa ini telah menuntut pelembagaan keuangan untuk
menjamin terselengaranya pemerintahan, seperti penggajian dan sebagainya.
- Penunjukan Pengganti Abu Bakr
Penunjukkan ‘Umar oleh Abu Bakr sebagai
penggantinya[25] juga tidak memiliki
landasan teologis dari teks keagamaan sebagai pembenar, namun penunjukan itu
bertujuan untuk menjaga keutuhan umat yang harus tetap dipertahankan mengingat
kondisi saat itu rentan perpecahan. Di sisi lain, ia sendiri merasa punya otoritas
untuk itu karena ia telah dipilih dan diserahi urusan umat, sehingga
penunjukkan ‘Umar merupakan bagian dari pelaksanaan tugasnya sekalipun tidak
ada preseden ketata negaraan seperti itu sebelumnya.
- Menolak Memberikan Tirkah Pada Fatimah
Abu Bakr menolak memberi tirkah Nabi berupa
tanah Fadak di Hijaz pada Fatimah karena tanah itu pemberian orang-orang Yahudi
sebagai tanda perdamaian antara umat Islam dengan orang Yahudi. Tanah itu tetap
di tangan Nabi hingga ia wafat. Namun kemudian Abu Bakr menarik tanah dari
putri Nabi dan memasukkannya sebagai income bayt
al-mal. Abu Bakr beristidlal
pada Hadis Nabi “Nahnu ma’ashir al-‘anbiya’ la nurith,
ma tarakna sadaqah.”[26] Di sisi lain negara
tidak mempunyai sumber pemasukan yang baik dan memadai, sehingga Abu Bakr
melakukan ijtihad itu sekalipun ia harus dimusuhi oleh Fatimah ra hingga
wafatnya.
- Menyamakanratakan Pembagian Harta Rampasan Perang
Abu Bakr menyamaratakan pembagian ghanimah
antara muhajirin dan ansar. ‘Umar berpandangan bahwa pembagian untuk kedua
golongan mestinya berbeda. La naj’al man taraka diyarahu
wa ‘amwalahu muhajiran ‘ila al-Nabi kaman dakhala fi al-Islam karhan. Tapi Abu Bakr berpendapat mereka masuk Islam
karena Allah dan pahalanya pada Allah. Bagian dunia cuma fasilitas. Di sini Abu
Bakr memutuskan persoalan ghanimah berdasarkan ra’yunya,[27] padahal semasa Nabi
hidup berkali-kali dipraktekkan cara pembagian ghanimah. Bisa saja Abu Bakr
punya pertimbangan-pertimbangan politis strategis yaitu sebagai
kompensasi bagi kesediaan kelompok Ansar menerima Abu Bakr sebagai khalifah,
padahal sebelumnya mereka menuntut secara tegas adanya pembagian kepemimpinan
antara golongan Muhajirin dan Ansar.
Ciri Utama Ijtihad Sahabat
Ada banyak hal yang menjadi ciri ijtihad
sahabat dengan generasi fuqaha’ sesudahnya. Muhammad Musa Tuwana mencatat
setidaknya ada enam[28]. Pertama adalah terletak pada pengendalian diri
mereka untuk tidak membuat prediksi hukum terhadap persoalan-persoalan yang
belum terjadi. Hal ini berbeda dengan kebiasaan fuqaha’ muta’akhkhirin. Para
sahabat hanya memberi fatwa hukum berkaitan persoalan yang telah terjadi. Sikap
para sahabat ini menunjukkan sikap realistis mereka dalam beragama.
Mereka tidak terbiasa menguras tenaga untuk sesuatu yang belum terjadi atau
bahkan mungkin sesuatu itu tidak akan pernah terjadi.
Kedua, persoalan-persoalan yang disandarkan
pada ra’yu masih sedikit dalam
ukuran yang relatif. Hal ini dikarenakan pergunaannya sangat terbatas, yaitu
hanya ketika tidak ditemukan nas yang tegas dari al-Qur’an dan Hadis. Ditambah
lagi keengganan para sahabat untuk menggunaakan ra’yu kecuali pada keadaan
terpaksa.
Ketiga, kemungkinan untuk berpindah/mengikuti
pendapat mujtahid lain sangat besar apabila ternyata pendapat yang lain
dianggap lebih dekat pada kebenaran. Keempat, perbedaan pendapat dalam periode
sahabat sangat kecil. Karena kesatuan mereka masih sangat kokoh di bawah
pengaruh para pembesar sahabat, khususnya pada kekhilafahan Abu Bakr dan Umar,
serta memungkinkannya melaksanakan musyawarah untuk menyatukan pandangan dan
menghindari perbedaan.
Kelima, kemampuan istinbat para sahabat
berdasarkan malakah fiqhiyah yang benar. Kemampuan itu mereka peroleh
karena kedekatannya dengan Nabi SAW yang memungkinkan mereka mengetahui sebab
turun ayat, sebab wurud Hadis, dan karena penangkapan mereka pada tujuan-tujuan
shari’ah, pengetahuan tentang illat hukum, memiliki dzawq bahasa Arab sehingga
cara istinbat mereka dilakukan tanpa menyebut kaidah-kaidah istikhraj al-hukm. Dan yang keKeenam, hasil ijtihad sahabat bisa menjadi sumber
independen menyerupai ijma’.
Kesimpulan.
Keterbatasan teks-teks keagamaan di satu sisi
dan melimpahnya permasalah yang baru yang notabene tidak memiliki “petunjuk
peraktis keagamaan menjadikan keharusan untuk melakukan ijtihad.
Keadaan ini sebenarnya merupakan salah satu
ciri keluwesan hukum Islam di dalam menjawab tantangan kemajuan umat manusia.
Sangat tidak mungkin persoalan yang merentang sepanjang sejarah dapat tercover
dalam nas, kecuali dalam bentuk memberi patokan-patokan nilai atau value. Untuk
itu ajaran Islam memberi ruang kosong (mantiq al-‘afw) bagi akal untuk berijtihad dalam batas-batas
yang sesuai denganmaqasid al-shar’i. Hal ini semuanya telah dipraktekan oleh para
sahabat sesuai dengan zuruf yang mereka hadapi. [*Oleh : A. Mufti
Khazin (Dosen Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya)
[1]Muhammad ‘Ali al-Sayis, Tarikh al-Fiqh al-Islamiyah (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1990), 52.
[2] Jalal al-Din ‘Abd al-Rahman al-Suyuti, al-Radd ‘ala Man akhlad ila al-ArdI wa Jahila ann al-Ijtihad fi kulli ‘Asr Fard (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1983), 67.
[3] Muhammad Musa Tuwana, al-Ijtihad wa mada hajatina ilayh fi hadh al-‘Asr(Kairo: Dar al-Kutub al-Hadithah, tt), 98.
[4] Muhammad Yusuf al-Qardawi, al-Ijtihad fi al-Shari’ah al-Islamiyah (Kuwait: Dar al-Qalam, tt), 65.
[5] Khalil ‘Abd al-Karim, al-Judhur al-Tarikhiyah li al-Shari’at al-Islamiyah(Beirut: al-Intishar al-‘Arabi, 1997), 104.
[6] Ahmad Saiful Anam, “Elastisitas Hukum Islam dalam menjawab Tantangan Zaman”, Orasi Ilmiyah pada Wisuda Sarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya ke 49 (Maret 2003), 2.
[7] Madhi Fadl Allah, al-Ijtihad wa al-Mantiq al-Fiqhi fi al-Islam (Beirut: Dar al-T{ali’ah, 1987), 45. Dan lihat Ahmad Ibrahim Bik, Tarikh al-Tashri’ al-Islami(Kairo: Dar al-Ansar, tt), 23.
[8] Muhammad Abu Zahrah, Tarikh al-Madhahib al-Islamiyah (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, tt.) 16.
[9] Muhammad Khalid Mas’ud, Islamic Legal Philosofy: A. Study of Abu Ishaq al-Shtibi’s Life dan Thought, terj. Yudian W. Asmin, Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial, (Surabaya: al-Ikhlas, 1995), 42.
[10] Tuwana, al-Ijtihad, 37.
[11] Ibid., 30.
[12] Bozena Gajane Strzyzewska, Tarikh al-Tashri’ al-Islami (Beirut: Dar al-Awqaf al-Jadidah, 1980), 360.
[13] Ibrahim Bik, Tarikh al-Tashri’, 16.
[14] Al-Sayis, Tarikh al-Fiqh, 43.
[15] Abu Zahrah, Tarikh, 74.
[16] Tuwana, al-Ijtihad, 37.
[17] Strzyzewska, Tarikh al-Tashri’, 39.
[18] Muhammad Zuhri, Hukum Islam dalam Lintasan sejarah (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), 37.
[19] Muhammad Ibn Isma’il al-Bukhari, S{ahih al-Bukhari, juz 3 (Beirut: Dar al-S{a’b, tt), 175.
[20] Maslahah adalah melahirkan suatu ketentuan berupa jalb al-manafi’ wa dar`u al-mafasid terhadap makhluk dengan menjaga maksud syari’at. Sedangkan Mursalahadalah sesuatu yang tidak mempunyai ketentuan dari teks keagamaan baik dalam menetapkannya (i’tibar) atau membatalkannya (ilgha`). Ibrahim Bik, Tarikh, 103.
[21] Al-Bukhari, S{ahih, juz 4, 257.
[22] Muhammad Husayn Haykal, al-S{iddiq Abu Bakr (Kairo: Dar al-Ma’arif, tt), 96.
[23] Ibid., 282.
[24] Jalal al-Din al-Suyuti, Tarikh al-Khulafa’ (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 74.
[25] Haikal, al-S{iddiq, 323-325.
[26] Fadl Allah, al-Ijtihad, 48.
[27] Ibid., 49.
[28] Tuwana, al-Ijtihad, 36-37.